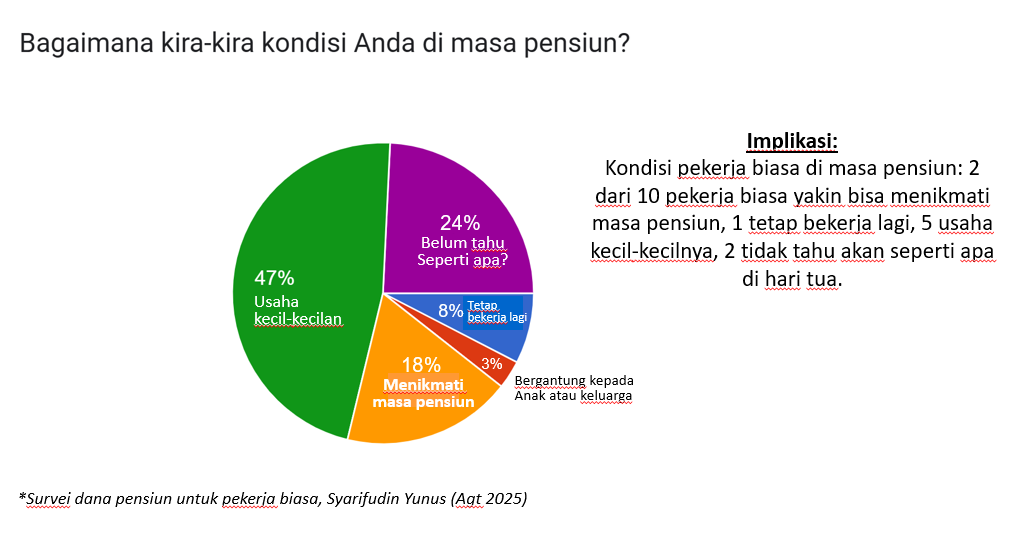Berislam Bersama Penderitaan
4 hari lalu
Kisah Amul Huzni mengajarkan bahwa iman juga merangkul luka, duka, dan penderitaan sebagai fitrah manusia.
Amul Huzni
Ada satu masa yang menjadi bagian dari perjalanan hidup Rasulullah saw. yang dapat kaum muslim renungkan lebih dalam lagi. Kisah yang biasanya kurang mendapatkan perhatian khusus, malah dianggap sebagai angin lalu. Pada tahun ke-10 kenabiannya, Khadijah selaku istri Rasulullah saw. dan Abu Thalib selaku pamannya meninggal dunia. Sebagaimana sifat jaiz yang ada pada setiap diri seorang nabi dan rasul Allah yakni al-a’radhulbasyariyyah (sifat manusiawi) Rasulullah saw. mengalami kedukaan yang sangat mendalam. Tradisi sejarah Islam menyebutnya sebagai amul huzni yang berarti tahun kedukaan.
Istilah khusus bagi waktu tersebut secara tidak langsung menegaskan sisi lain dari sang teladan zaman. Muhammad yang adalah manusia juga mengalami kesedihan yang mendalam; berpisah dengan kekasih tercintanya dan ditinggalkan oleh pelindung setianya. Tentu masa ini menjadi hari-hari yang panjang lagi melelahkan. Begitu juga akibatnya, jaminan keamanan memudar hingga sang Nabi terus menerus terpapar kekerasan. Sekalipun dia pergi ke Thaif malah mendapatkan penolakan. Jauh sebelum itu, Nabi dan keluarga menjadi target pemboikotan kaum Quraisy sampai menyebabkan kekurangan pangan, yang mungkin adalah satu di antara pemicu wafatnya Khadijah binti Khuwailid.
Umat muslim sering kali diajak cepat-cepat melewati penggalan kisah ini menuju pada peristiwa Isra Mikraj. Masa berkabung perlu juga dihayati. Sebuah ibrah kiranya hendak mengungkapkan bahwa ada bagian dari kehidupan yang menunjukkan bahwa waktu terus bicara duka demi duka. Tahun kedukaan Nabi berada di ambang derita dan derita, baik penyebab maupun akibatnya. Begitulah adanya. Lagi pun hal ini bukan yang pertama bagi Nabi, kesendirian bukanlah barang asing. Sejak lahir dia sudah menjadi yatim. Bahkan Muhammad kecil mesti berpisah lebih awal dengan ibunda dan kakek tersayang yang mendahuluinya meninggal dunia.
“Namanya juga Nabi, pasti ujian hidupnya lebih berat.” Umat cenderung diajarkan untuk menarik kesimpulan model ini, tanpa diberi pengertian, pengakuan, validasi, dan ruang untuk mengalami dengan jujur beberapa kenyatan hidup yang getir.
Islami Tidak Harus Toxic Positivity
“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” (Al-Balad: 4)
Orang-orang pada umumnya memandang bahwa segala bentuk penderitaan hidup tak lebih dari sekedar realitas yang semu. Di depan sana, semacam ada janji akan harapan yang pasti bahwa hidup akan lebih baik. Oleh karena itu, pandangan demikian kerap menyangkali pengalaman manusiawi yang bergumul bersama pilu dan kesengsaraan. Seakan-akan kepedihan hidup harus dihindari dan disangkal. Kehidupan dibayangkan sebagai perjalanan yang selalu dan harus menyenangkan. Berulang-ulang di majelis-majelis terdengar “bersabarlah!” “harus banyak-banyak bersyukur”.
Padahal dalam tauhid yang umat muslim yakini ditegaskan bahwa Allah merupakan satu-satunya Zat yang Mahasempurna. Allah bersifat Baqa yang berarti kekal. Manusia sebagai makhluk Allah justru memiliki sifat yang berkebalikan.Manusia menuju pada kefanaan, artinya berproses ke arah kerusakan. Dengan begitu ketidaksempurnaan merupakan fitrah yang melekat pada diri manusia, termasuk kepastian dalam mengalami penderitaan hidup. Manusia juga disebut sebagai tempat dari segala salah dan lupa seperti yang ditegaskan oleh kaul terkenal, al-insanu mahalu khato wannisyan. Hal tersebut sekali lagi menegaskan bahwa manusia tidak selamanya memiliki kondisi yang positif. Menjadi manusia tidak mesti baik-baik saja.
Kalangan salaf meyakini bahwa penderitaan merupakan ujian hidup (ibtila’) yang disikapi dengan kepasrahan atas kehendak Allah yang mutlak. Sedangkan kalangan khalaf terbagi menjadi dua pandangan; asy'ariyah lebih melihat penderitaan sebagai qadha qadar Allah dan manusia hanya mengusahakan (kasb), sejalan dengan itu maturidiyah juga mempercayainya dengan kecenderungan penegasan pada manusia yang bertanggung jawab atas amalnya melalui akal untuk memahami penderitaan. Berbeda dengan itu mu'tazilah memandang penderitaan sebagai konsekuensi dari perbuatan kebebasan manusia, sebab Allah tidak mungkin menciptakan kezaliman. Semua ini menunjukkan bahwa sejak masa klasik, percakapan kalam tentang sumber kebermulaan penderitaan telah menjadi salah satu tema yang serius.
Melanjutkan jalan ikhtiar, teologi hari ini perlu mendaratkan diskursusnya pada problem yang relevan dengan keseharian umat. Melampaui rumusan langitan, teologi semestinya membangun ruang religius yang ramah bagi orang yang hidup dengan masalah penderitaan. Keberimanan seseorang tidak serta merta harus diperselisihkan secara kontras dengan situasi mental apalagi pengalaman traumatik. Islami tidak harus toxic positivity, yang semena-mena menuntut hidup seorang beriman harus selalu baik-baik saja. Ajaran Islam akan selalu mengupayakan kemaslahatan bagi setiap insan. Termasuk menyediakan jalan beriman bersama penderitaan, yang tidak perlu mendamaikannya dengan pencarian akan jawaban teologis yang tunggal. Namun dengan kemampuan untuk menapaki penderitaan sebagai fitrah kehidupan.
Islam tentu menghargai manusia, juga pengalaman hidup menderita yang menyertainya. Pada kasus penerimaan terhadap segala persoalan hidup yang memilukan, mungkin teologi harus memberi keheningan sejenak sebagai jawabannya. Hal tersebut juga merupakan pengamalan atas ayat alladzina yu’minuna bil-ghaibi (Albaqarah : 3). Kegaiban merupakan misteri yang harus direngkuh oleh orang-orang yang beriman, banyak hal-hal yang tidak terjangkau selain surga, neraka, malaikat, dan hari kiamat.
Melalui ini, islam akan dipahami lewat kekhasan pengalaman insan yang menderita, dengan mengizinkan luka, trauma, dan pilu untuk membangun pandangan religiusitas yang baru. Sebagaimana pada klasik mengurai cara memahami Islam, di samping burhani (pendekatan rasional, logis, ilmiah) dan bayani (pendekatan teksual wahyu), mungkin cara irfani yang menempatkan hati, intuisi, dan pengalaman spiritual menjadi lebih arif untuk menempatkan penderitaan. Merasa-rasa luka batin sebagai pengalaman penderitaan melampaui aqli (akal) dan naqli (teks) untuk menjangkau Allah Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Melampaui segala tafsir dan ijtihad segala zaman, biarlah iman yang meraba-raba sebagai bentuk kasyaf untuk menemukan kembali penderitaan itu sebagai apa adanya. Mencari jalan pulih dengan cara yang sama sekali berbeda dari biasanya.
Bagi para insan yang terluka mungkin penderitaan tidak akan pernah menjumpai akhirnya. Biarlah itu semua menjadi kehendak Allah yang penuh dengan teka-teki. Manusia hanya bisa memberi makna bagi penderitaan yakni di antara azab dan cobaan, atau entah bukan keduanya. Penderitaan adalah penderitaan itu sendiri, yang tidak bermakna lain, yang sejak lama diarungi oleh para mutakalimin. Terlepas dari mana asalnya, terlepas juga dari jawaban yang menujukkan kecenderungan akan keadilan, kebaikan, atau kekuasaan Ilahi, penderitaan itu nyata adanya juga pedih dan menyakitkan. Doa dan pelukan hangat untuk orang-orang yang hidup dengan kemiskinan, adiksi, depresi, trauma, soliter, dan kerapuhan lainnya.
Di sini mengulik kebebasan beragama, dialog lintas iman, dan teologi
0 Pengikut

Berislam Bersama Penderitaan
4 hari laluBaca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0







 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 98
98 0
0